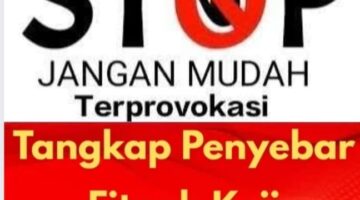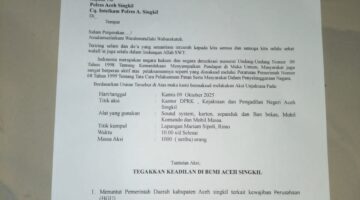BANDA ACEH | Dua dekade setelah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), korban konflik di Aceh kembali menyuarakan tuntutannya kepada pemerintah. Dari Aceh Utara, mereka mengajukan enam tuntutan utama sebagai bentuk pengingat bahwa pemulihan pasca-konflik belum sepenuhnya tercapai.
Koordinator Forum Komunikasi Korban dan Keluarga Korban Tragedi Simpang KKA (FK3T-SP.KKA), Murtala, menegaskan bahwa keadilan bagi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masih jauh dari harapan. Hingga saat ini, negara belum melakukan pendataan menyeluruh terhadap korban konflik yang tersebar di 16 kabupaten/kota di Aceh.
“Semua peristiwa pelanggaran HAM berat seperti Tragedi Simpang KKA, Rumoh Geudong, Jambo Keupok, dan lainnya harus diakui secara resmi oleh negara. Lebih dari itu, negara wajib menindaklanjutinya melalui proses hukum yang adil,” kata Murtala, Senin, 18 Agustus 2025.
Tuntutan pertama adalah pendataan korban secara menyeluruh. Hingga kini, jumlah korban konflik yang tercatat resmi masih terbatas, padahal ribuan orang pernah mengalami penyiksaan, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, hingga pembunuhan selama konflik.
Tuntutan kedua adalah penyelenggaraan pengadilan HAM berat. Korban menekankan perlunya proses hukum yang sesuai prinsip keadilan, disertai jaminan hak atas restitusi, rehabilitasi, dan kompensasi tanpa diskriminasi maupun pungutan ilegal.
Tuntutan ketiga adalah pengesahan dan implementasi Qanun Pemulihan Korban Konflik. Para korban mendesak adanya dasar hukum yang jelas di tingkat daerah, termasuk layanan konseling berkelanjutan, program pemberdayaan ekonomi, dan pelatihan keterampilan. Anak-anak korban, khususnya yatim piatu, anak syuhada, dan yang putus sekolah, harus dijamin mendapat beasiswa, pendidikan layak, dan modal usaha.
Selain tiga tuntutan tersebut, korban juga menekankan perlunya pengakuan resmi terhadap semua pelanggaran HAM berat, perlindungan hukum bagi saksi dan keluarga korban, transparansi dalam implementasi kebijakan pemulihan, serta keterlibatan masyarakat sipil dalam monitoring proses tersebut.
Suara korban Aceh ini menjadi pengingat bahwa upaya pemulihan pasca-konflik tidak cukup hanya di atas dokumen formal, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata pemerintah. Pemenuhan tuntutan ini diharapkan mampu memberikan keadilan dan mendorong rekonsiliasi yang berkelanjutan di Aceh. (*)